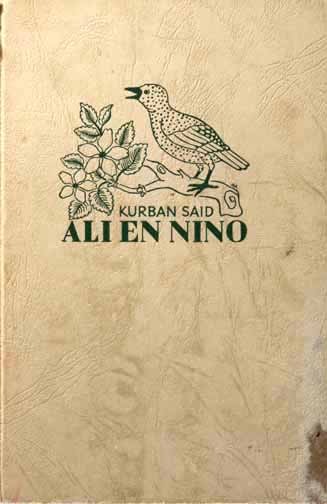Saya belum menonton film Dilan. Di tengah kehebohannya, saya justru mengingat-ngingat film cinta lain yang kerumitannya jauh di atas Dilan: ‘Ali and Nino’. Kalau Dilan ibarat chips renyah, Ali and Nino ini boleh dibilang cheesecake campur lapis legit ditambah taburan coklat asem manis (apa coba rasanya?). Kompleks dah, pokoknya.
Salah satu film Indonesia yang lumayan mendekati kerumitannya adalah ‘3 Hati, 2 Dunia, 1 Cinta’ –kombinasi sempurna novelet Ben Sohib dan kumpulan puisi WS Rendra yang dijadikan film. Tapi, kalau film ini baru sampai urusan agama, ‘Ali and Nino’ sudah masuk wilayah urusan negara.

Mirip dengan pertemuan saya dengan novelet Ben Sohib yang bikin saya ngangak sendirian di depan rak buku Gramedia sesiangan, saya mendapati novel ‘Ali dan Nino’ teronggok di sebuah pameran buku terkemuka di Jakarta sekitar sepuluh tahun lalu. Waktu itu saya masih bujang, berkantong kering, dan hanya bisa berkeliaran sendirian dari pagi sampai sore di pameran buku demi ngubek-ngubek buku murah. Bukan yang di rak buku, tapi yang sudah acak-acakan di tumpukan ‘Sale’, ‘Diskon’, dan ‘Banting Harga’. Saat itu, harga novel ‘Ali dan Nino’ dibanting ke angka Rp 10.000 per eksemplar. Sama harganya dengan kumpulan ceperen Danarto, “Adam Ma’rifat”. Gila, pikir saya. Nampaknya, selera pasar satu dekade belakangan memang kurang berkualitas. Menurut salah satu editor penerbit buku terkenal yang saya sodori naskah, “Sekarang, pasar butuh yang ringan-ringan.” Yang tinggal lep, gitu. Dia mengatakannya sambil breaking bad news, memberikan kabar duka ke saya. “Naskah Mas ini bagus. Tapi, marketing bilang pasarnya nggak oke.” Itu, rasanya mirip Mas Anang bilang “aku sih iyes”, tapi Om Dhani dan Papa Bebi nyerocos kritik nggak berhenti-berhenti.
Setelah membaca sedikit cuplikan ‘Ali dan Nino’, saya langsung memutuskan untuk membelinya. Kapan lagi membeli buku bagus yang sudah diterjemahkan ke 30 bahasa ini dengan harga murah meriah?
‘Ali dan Nino’ bukan novel bau kencur. Ia sudah terbit sekitar tahun 1937 di Vienna. Penulisnya misterius. Ia memakai nama Kurban Said –yang boleh diartikan sebagai Pengorbanan untuk Kebahagiaan. Persis dengan isi bukunya. Bahkan, boleh jadi pseudonym yang dipakainya lebih cocok sebagai judul novelnya. Bertahun-tahun orang berdebat tentang siapa tokoh asli di balik nama Kurban Said. Ya, mungkin debatnya nggak seseru debat Pilkada sih yang dimasukin ke hati. Ada yang menghubungkannya dengan Lev Nussimbaum, seorang Yahudi-Jerman yang belakangan masuk Islam dengan nama pena Essad Bey. Ada pula yang mengaitkannya dengan Yusif Vazir Chamanzaminli, seorang penulis Azerbaijan yang juga menerbitkan banyak cerita pendek dan esai. Tidak ada kata sepakat. Tetapi, siapapun di balik nama Kurban Said, novel ‘Ali dan Nino’ memang menarik.
Tahun 2016, novel ini diangkat ke layar lebar setelah –konon– beberapa dekade menemui halang- rintang, melewati lembah-bukit, dan menyurusi onak-duri. Katanya, banyak yang harus dipertimbangkan. Setidaknya, ada tiga kultur yang ditampilkan: Azerbaijan, Georgia, dan Iran. Dua agama yang disatukan asmara: Islam (Syi’ah pula, alamak) dan Kristen Timur Ortodoks. Di balik kesusahpayahan produksinya, film ini semestinya menjadi film etnografis yang kaya meskipun hanya menampilkan aktor dan aktris medioker.

Ceritanya, Ali Khan Sirvanshir (diperankan cukup baik oleh Adam Bakri yang tidak punya hubungan apapun dengan Oemar Bakri) adalah jejaka muslim yang tumbuh dalam budaya Barat di Baku, di tengah kecamuk Perang Dunia I. Ayahnya boleh dibilang raja. Kaya, terhormat, borju. Maka, Ali pun mendapat pendidikan bagus –semacam sekolah internasional berkurikulum Rusia dan SPP-nya selangit. Sebagai jejaka, matanya tertarik pada gadis cantik Georgia, Nino (diperankan Maria Valverde). Jangan bayangkan Ali mirip Dilan yang suka nge-gombal. Ali tumbuh di masa perang. Jadi, kalau dia menyukai gadis, satu-satunya pilihan adalah: menembak. Tepat di hatinya, tak boleh meleset. Bilang ke orangtua, “Aku ingin menikahinya!” Gitu. Pemuda jaman perang mah straight, nggak suka belok-belok.
Sayangnya, Nino si gadis pujaan ini lahir di keluarga Kristen ortodoks yang membuat ayah Ali ragu-ragu. Tapi, ternyata asmara itu tak dapat ditahan. Berat hatinya sebelum secara implisit memberi lampu hijau buat Ali. Repotnya, Perang Dunia I tengah berkecamuk. Ali dan keluarganya adalah ningrat di Baku, pemegang tampuk kekuasaan tradisional yang belakangan dikenal sebagai negara Azerbaijan. Nino dan keluarganya adalah darah biru di Tbilisi, pengatur kerajaan kecil tradisional yang kemudian pecah dari Rusia dan diberi nama Georgia. Setelah bertemu, ayah Nino yang tak kuasa menahan hasrat asmara jejaka-gadis meminta mereka menunda rencana pernikahan. “Bersabarlah. Setidaknya, sampai perang reda,” katanya. Ayahnya tipe politisi safe player. Di titik seperti itu, kita tidak bisa benar-benar membedakan antara bijak dan penakut.
Perang memang bukan hanya merusak tatanan makro negara, tetapi juga urusan mikro percintaan dan pernikahan. Jangan bayangkan urusan asmara anak muda milenial. Asmara Ali dan Nino ini menjadi pelik karena Ali –sebagai keluarga ningrat– harus mempertaruhkan cintanya di tengah peliknya masalah politik. Lebih dari itu, Malik –temannya yang seorang Armenia– datang tanpa diduga, memendam harsat pada Nino dan menculiknya untuk memaksa keluarga Nino di Tbilisi untuk bergabung dengan Rusia dan tidak memecahkan diri sebagai sebuah Negara.

Ali mengejar Malik dengan kuda –karena ia bukan anak geng motor. Berkelahilah mereka tanpa ada guru yang melerai dan setrap. Malik terbunuh. Dalam tradisi Armenia, nyawa harus dibayar nyawa. Nggak boleh dicicil. Nggak peduli pula siapa yang salah. Maka, sebelum nyawanya dihabisi, Ali Khan dipaksa mengungsi. Ia pergi jauh ke Dagestan dan meninggalkan Nino dalam pedih yang bertumpuk-tumpuk. Dalam tradisi Georgia, gadis yang sudah dibawa lari jejaka lain sudah tak pantas lagi dinikahi. Derajatnya meluncur deras ke bawah, tak bersisa martabatnya. Satu-satunya jalan menikah, ya sama Ali –yang kini minggat jauh.
Pemandangan gunung bersalju menjadi latar yang cantik sepanjang perjalanan Ali ke Dagestan. Jangan tanyakan bagaimana Ali memendam kegundahannya. Lebih dari Nino, ia bukan saja kehilangan cerita asmara, tetapi tak mampu bersama-sama berjuang memerdekakan Azerbaijan bersama keluarga besarnya. Padahal, itulah cita-cita terbesarnya sebagai lelaki. Seberapapun besar asmaranya, negara ada di atas segala-galanya.
Tanpa diduga, Nino memaksa dan memberanikan diri menyusul Ali ke Dagestan. Mereka berjumpa. Dua hati menyatu lagi. Sekali itu berjumpa, mereka langsung menikah di depan pemuka agama. Nggak pake ditanya KTP, Kartu Keluarga, apalagi wali nikah. Eh, tapi agama mereka kan beda. Jangan bayangkan cerita ini akan berakhir bahagia dengan ada yang melunak untuk berpindah keyakinan karena cinta. Jangan pula disimplifikasi dengan cara berpisah diiringi background nyanyian ‘cinta itu tidak harus memiliki’. Saat ditanya apakah mau berpindah agama, Nino menggeleng. Batal nikah? Nggak. Ali yang muslim Syiah menikahi Nino yang Kristen Ortodoks. Tanpa surat nikah, tanpa wali nikah. Apalagi gaun pengantin endorse-an dan liputan live infotainment. Jangan pula tanyakan apakah pernikahan itu sah atau tidak. Pertama, sah menurut agama siapa? Kedua, tak penting pula bagi keduanya. Kesepakatan yang lebih tinggi bagi mereka justru sudah dibuat: Ali akan kembali bertempur untuk kemerdekaan Azerbaijan –betapapun berseberangannya dengan keputusan keluarga Nino.

Politik dan ideologi –pada situasi tertentu, menjadi begitu saklek dan berdiri di atas apapun. Pada titik itu, cinta kepada tanah air, kerajaan, dan kekuasaan adalah muara dari segalanya. Cinta istri dan keluarga menjadi pendorong, bukan perongrong. Bahkan, ketika keadaan menjadi semakin pelik, perang berkepanjangan, dan situasi tidak terkendali, Nino harus rela diungsikan ke Iran –tempat keluarga besar Ali berdiam.
Iran di masa Perang Dunia I ada di persimpangan jalan, dihimpit dua kuasa besar: Inggris dan Rusia. Barangkali, itu untungnya buat Ali dan Nino. Iran relatif adem ayem karena terpaksa netral. Tapi, bagi Nino, hidup di Iran adalah neraka. Dalam tradisi muslim Iran, ia tak boleh keluar rumah sendirian. Disediakan pula baginya pembantu laki-laki yang sudah dikebiri –tak berhasrat. Sekali keluar rumah, ia harus memakai kerudung dan menutup aurat. Kultur yang sama sekali berbeda dan tak pernah terbayangkan sebelumnya ketika ia melihat Ali. Ya, nggak kelihatan karena Ali memang rada sekuler-borju. Wong nikah sama Nino saja dilakoni dengan suka cita. Eh, ternyata keluarga besarnya di Iran ini saklek: fundamentalis, tapi bukan teroris. Pelajaran penting: sebelum menikah, perlu observasi yang komprehensif dan holistik.
Nino tak sangup. Ia melambaikan tangannya ke kamera.
Ali, berkat tempaan long distance relationship, memiliki telepati yang mumpuni untuk merasakan kegundahan sang belahan hati.
Sebentar mereka bertemu, pasukan Rusia sudah keburu masuk ke daerah Azerbaijan. Bagi Rusia, Azerbaijan adalah kaum separatis. Bagi Azerbaijan, Rusia adalah kolonialis. Jadi, urusan hidup ini memang urusan cara pandang. Dari mana kita memandang, dengan apa kita memandang.
Ali kembali memanggul senjata dan bergabung dengan kakak dan sepupunya.”Hati-hati, Bang,” kata Nino. “Sekarang udah ada anak kita.” Bukan Ali tak ingin Nino menjanda dan menghidupi anaknya sebatang kara, tetapi cinta dan cita-cita terbesarnya tak bisa ia ungkiri lagi. “Azerbaijan harus merdeka,” katanya. Kisah ini berlanjut, tentu tidak seperti film Merah Putih atau Darah Garuda yang jagoannya menang melulu walaupun kalah kelas senjata. Walaupun bisa adu taktik, pasukan Rusia jelas menang segalanya. Jumlah pasukannya, amunisinya. Dan Ali, ia memutuskan bergabung dengan pejuang lainnya. Mati di tengah pertempuran.

Ia gagal menjadi bagian dari kemerdekaan Azerbaijan. Tapi, setidaknya, keberaniannya telah menjadi inspirasi rakyat Azerbaijan untuk terus berjuang tanpa henti. Perang berlanjut. Nino mengungsi semakin jauh bersama keluarganya ke Inggris. Untungnya, Perang Dunia I menyurut. Rusia melemah. Rakyat Azerbaijan memanfaatkan situasi untuk memerdekakan diri bersama banyak pecahan negara lainnya. Di ujung kisah ini, kita boleh saja berandai-andai: kalau saja Ali mau bersabar…
Tapi ya sudahlah. Kurban Said sudah cukup mengingatkannya bahwa seorang Ali pernah ada untuk Nino, Azerbaijan, dan barangkali juga kita.
Rotterdam, sambil nonton Chelsea vs Barcelona.